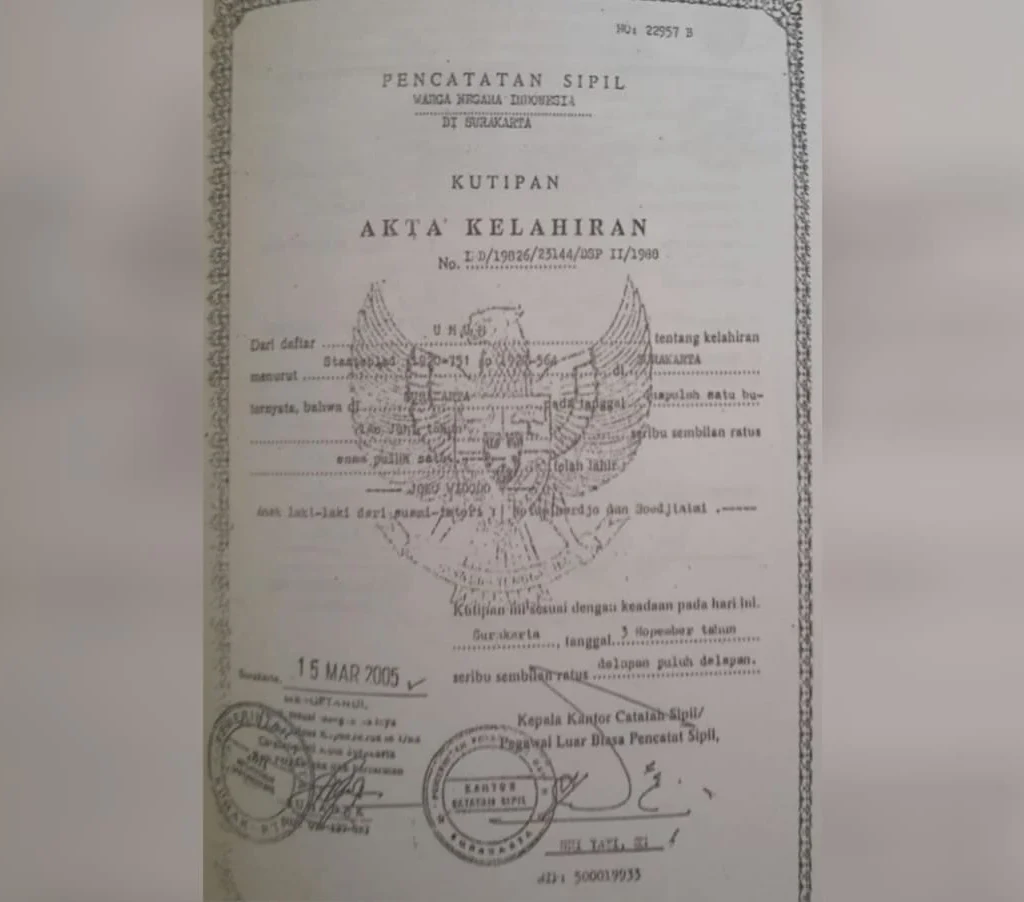Eramuslim.com – Pada akhir 1941 hingga awal 1942, dunia menyaksikan serangkaian serangan masif oleh Jepang terhadap pangkalan-pangkalan militer Sekutu. Pearl Harbour, Hong Kong, dan Malaya menjadi sasaran pengeboman. Di Hindia Belanda, serangan itu menjalar ke Sumatra Selatan, kemudian ke pantai utara Jawa, termasuk Eretan, Indramayu. Tak butuh waktu lama, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang, pada 8 Maret 1942.
Kekalahan Belanda membawa gejolak sosial. Penjarahan terhadap toko-toko milik orang Tionghoa marak terjadi, menyusul anggapan bahwa mereka adalah sekutu kolonial Belanda. Kerusuhan meluas dan memicu amarah rakyat yang lama terbelenggu kemiskinan. Dalam kekacauan itu, rumah dan pabrik milik etnis Tionghoa dijarah. Dari 130 pabrik gula di Pulau Jawa pada 1940, hanya 32 yang tersisa. Kerugian mereka ditaksir mencapai 100 juta gulden. Nama-nama besar seperti Tjung See Gan, Hioe Nyan Yoeng, dan Tan Hoan Kie mencatat kerugian ratusan ribu gulden.
Jepang, yang kini berkuasa, juga mencurigai etnis Tionghoa sebagai pihak pro-Barat. Mereka membubarkan partai-partai seperti Kuomintang dan Chung Hwa Hui, serta menangkapi tokoh-tokoh Hoakiau di seluruh kota besar. Sebanyak 542 orang Tionghoa ditahan di kamp konsentrasi Cimahi. Penangkapan dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk kepada mereka yang menikah dengan orang Belanda atau mengadopsi nama khas Eropa.
Meski demikian, tak semua Tionghoa ditahan. Jepang menerapkan sistem pendaftaran wajib untuk mengawasi populasi mereka. Setiap yang terdaftar diberi kartu identitas setelah bersumpah setia kepada Kaisar. Biaya pendaftaran mencapai ƒ 50. Dalam upaya menenangkan komunitas Tionghoa dan menghindari pemberontakan, Jepang membentuk organisasi Hua Ch’iao Tsung-hui (HTCH) yang berfungsi sebagai penyalur bantuan sosial dan pelestari budaya dagang Tionghoa.
Kesaksian tentang penderitaan etnis Tionghoa banyak tercatat dalam memoar dan buku sejarah. Salah satu yang paling terkenal adalah buku “Dalem Tawanan Djepang” karya Nio Joe Lan, mantan jurnalis surat kabar Keng Po dan Sin Po. Ia menceritakan bagaimana dirinya, bersama tahanan lain, mengalami kondisi memprihatinkan di kamp Bukit Duri, Serang, dan Cimahi. Di Bukit Duri, tawanan tidur bertiga dalam sel sempit dan hanya mendapat satu kali makan nasi dan air kangkung sehari. Perbedaan perlakuan rasial pun terasa: tawanan Belanda mendapat jatah makanan lebih baik.
Namun, situasi di Cimahi sedikit berbeda. Para tahanan hidup seperti di kota kecil, dengan kebebasan terbatas. Mereka bisa bercocok tanam, berdagang, hingga membentuk orkes musik dan layanan masyarakat berdasarkan keahlian. Bahkan komunitas Freemason yang ditahan di sana berhasil mendirikan loji darurat bernama De Beproeving.
Salah satu tokoh penting yang wafat di kamp ini adalah Khouw Kin An, Mayor Cina terakhir Batavia. Kisah lainnya menyebut penganut Freemason dari Bandung yang juga wafat di kamp ini, dimakamkan dengan ritual masonik.
Nestapa etnis Tionghoa di masa pendudukan Jepang menjadi lembar kelam yang tak bisa diabaikan. Dari penjarahan massal, penahanan tak manusiawi, hingga diskriminasi rasial, semuanya menunjukkan betapa komunitas ini menjadi korban dalam pusaran perang dan politik identitas. Memoar seperti milik Nio Joe Lan adalah pengingat abadi bahwa sejarah luka harus dikenang agar tak terulang.
Sumber: Tirto.Id